Jakarta – Dunia tengah menyaksikan lonjakan investasi besar-besaran pada pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI). Menurut proyeksi Morgan Stanley, sekitar $3 triliun (Rp46.200 triliun) akan digelontorkan hingga 2029, dengan separuhnya untuk pembangunan fisik dan separuh lainnya untuk perangkat keras berteknologi tinggi. Angka ini setara dengan ukuran ekonomi Prancis pada 2024.
AI data centre berbeda dari pusat data konvensional. Untuk melatih model bahasa besar (LLM), ribuan chip Nvidia bernilai sekitar $4 juta per kabinet ditempatkan rapat guna meminimalisasi jeda pemrosesan. Kepadatan ini memungkinkan parallel processing, namun juga mengonsumsi listrik dalam skala gigawatt, dengan lonjakan daya setara ribuan rumah menyalakan peralatan secara bersamaan.

Tantangan energi menjadi isu utama. CEO Nvidia, Jensen Huang, bahkan menyarankan penggunaan turbin gas khusus “off the grid” agar beban listrik masyarakat tidak terganggu. Di sisi lain, raksasa teknologi seperti Microsoft, Google, dan Amazon berlomba berinvestasi pada energi terbarukan dan nuklir untuk mendukung operasional mereka.
Selain energi, kebutuhan air sebagai pendingin chip menimbulkan kontroversi. Di AS, negara bagian Virginia mempertimbangkan aturan baru soal konsumsi air pusat data. Sementara rencana pembangunan “AI factory” di Lincolnshire, Inggris, mendapat penolakan Anglian Water karena khawatir pasokan air minum terganggu.
Meski nilainya fantastis, sejumlah pakar mengingatkan risiko “bubble” investasi. Zahl Limbuwala, analis di DTCP, menyebut fenomena “bragawatts” menggambarkan kecenderungan industri melebih-lebihkan skala proyek. “Investasi harus menghasilkan imbal balik, jika tidak pasar akan mengoreksi diri,” ujarnya.
Namun ia menekankan, berbeda dengan gelembung dotcom, pusat data AI adalah aset nyata. Dengan dampak AI yang diprediksi melampaui internet, kebutuhan infrastruktur masif ini dinilai tetap memiliki dasar kuat—meski ledakan belanja tak akan berlangsung selamanya.








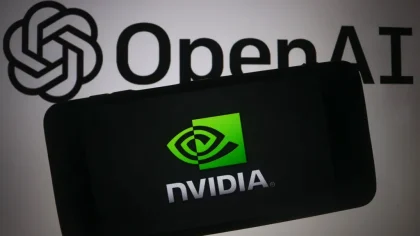







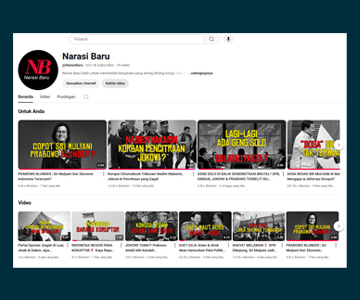




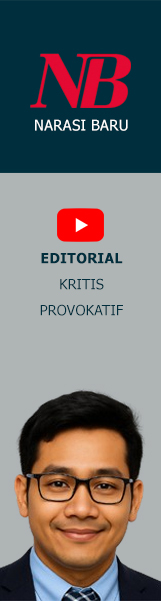
Komentar