Upaya menjelaskan apa itu kecerdasan buatan generatif (generative AI) kerap melahirkan berbagai analogi. Mulai dari “kotak hitam”, “autocomplete super”, hingga “burung beo”. Salah satu yang kini populer adalah sebutan “kalkulator kata”, istilah yang juga dipopulerkan CEO OpenAI, Sam Altman.
Analogi ini menggambarkan bahwa, sebagaimana kalkulator menghitung angka, AI generatif menghitung pola bahasa dari data dalam jumlah besar. Namun, perbandingan ini juga menuai kritik. Kalkulator tidak punya bias, tidak membuat kesalahan, dan tidak menimbulkan dilema etis—hal yang jelas membedakannya dari AI.
Meski demikian, esensi dari AI generatif memang terletak pada praktik “menghitung” bahasa. Bahasa manusia sendiri penuh perhitungan statistik tersembunyi. Kita terbiasa mendengar “salt and pepper” ketimbang “pepper and salt” karena frekuensi penggunaan, bukan karena aturan tata bahasa kaku. Pola-pola semacam ini, yang dalam linguistik disebut collocations, ditiru oleh AI.
Keberhasilan model bahasa besar (LLM) seperti GPT-5 dan Gemini adalah kemampuannya meniru rasa “natural” itu. Dengan menghitung probabilitas kata, simbol, atau tanda, AI menghasilkan rangkaian yang terasa wajar, bahkan kerap menipu intuisi manusia.
Namun, penting dicatat: AI tidak “berpikir” atau “memahami”. Ia hanya menghitung kemungkinan urutan kata berdasarkan data. Meski dapat menulis kalimat “I love you”, AI bukanlah “aku” atau “kamu”, dan tidak memahami makna cinta.
Generative AI hanyalah sistem penghitungan pola bahasa tingkat lanjut. Kesalahpahaman muncul karena narasi pemasaran perusahaan teknologi yang kerap menyebut AI “berpikir” atau “bermimpi”. Padahal, hingga kini, ia tetap sekadar kalkulator—bukan kesadaran baru.



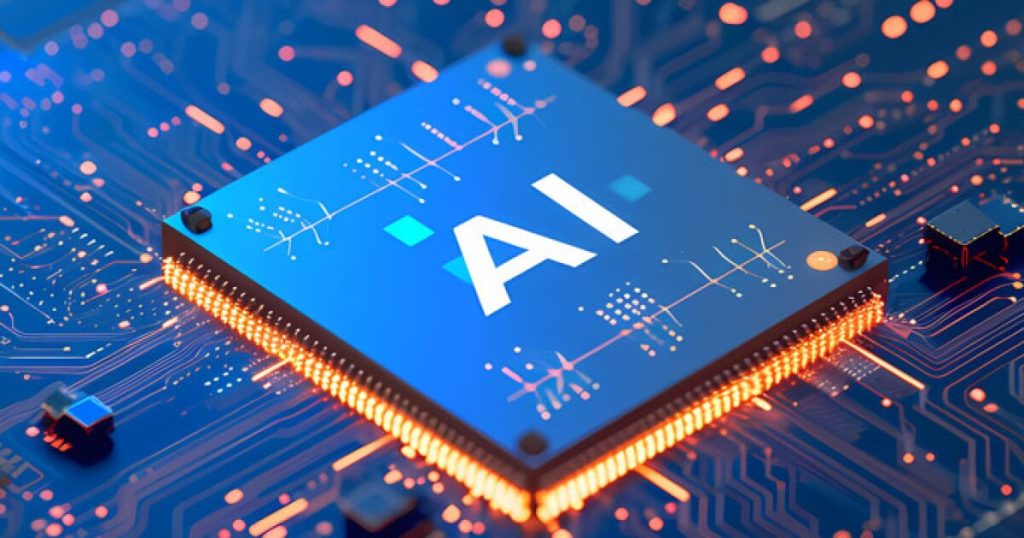





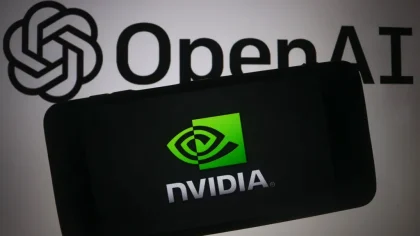






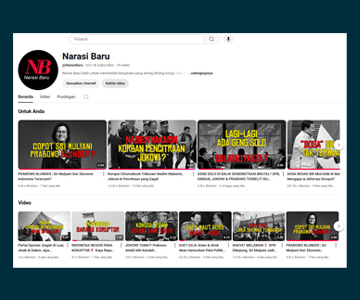




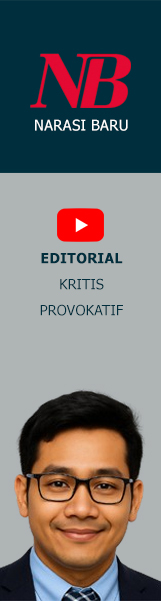
Komentar