Jeritan Sunyi dari Relawan Bergizi Dapur Pondok Melati
Bapak yang terhormat,
Surat ini lahir bukan dari pena, melainkan dari kepulan uap dapur yang menatap langit pagi dengan dada sesak. Kami menulis dari antara denting panci dan riuh ompreng, dari balik seragam lusuh yang menampung peluh dan sabar. Kami bukan pejabat, bukan pegawai, bukan pula pemilik tanda tangan di bawah kop surat kementerian. Kami hanyalah relawan — mereka yang datang dengan hati, bukan dengan kontrak.
Setiap hari kami menanak masa depan. Di dapur yang kecil, kami menyalakan api demi menghangatkan generasi yang belum tahu arti kenyang. Kami memotong sayur dengan tangan yang gemetar, bukan karena lapar, tetapi karena takut salah menakar. Kami mencuci ompreng yang penuh sisa nasi dan minyak, sementara mata kami menyimpan letih yang tak pernah diizinkan istirahat.
Kami tahu, negara mencita-citakan anak-anak yang sehat dan bergizi. Kami di sini, Bapak, adalah penjaga cita-cita itu. Tapi di balik setiap uap nasi, ada pedih yang tak pernah dicatat dalam laporan bulanan. Kami bukan mesin. Kami manusia yang punya keluarga di rumah — anak-anak yang menunggu, orang tua yang sakit, dan tubuh yang perlahan terkikis oleh kerja tanpa jaminan.
Bapak, kami ini relawan, tapi bukan berarti kami harus hidup tanpa perlindungan.
Kami bekerja di dapur yang panas, membawa logistik yang berat, mengantar makanan di jalan-jalan berlubang, menanggung risiko luka, tersiram minyak panas, atau terjatuh saat tergesa-gesa memenuhi target waktu.
Kami butuh jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan sosial untuk keluarga kami di rumah. Sebab tubuh kami adalah alat perjuangan bangsa ini, dan setiap alat perjuangan seharusnya dijaga, bukan dibiarkan rapuh.
Kami tunduk pada aturan, Pak. Kami berusaha mematuhi setiap prosedur: SOP, SLHS, HACCP, bahkan memastikan kehalalan di setiap tahap kerja kami. Kami bukan sekadar pengaduk sayur atau pengantar nasi — kami penjaga kepercayaan umat, penjaga kehormatan negara yang ingin anak-anaknya tumbuh dengan tubuh yang kuat dan jiwa yang jujur.
Namun di lapangan, kami sering dihadapkan pada perlakuan yang menihilkan martabat. Kami dibentak, disalahkan, dianggap lamban, seolah hati kami tidak ikut bekerja di setiap sendok nasi yang kami tuangkan.
Padahal, apa artinya pengabdian tanpa penghargaan? Apa artinya cinta pada negeri jika kami dibiarkan seperti bayangan yang bekerja di bawah cahaya kekuasaan, tapi tak pernah disebut dalam doa pembangunan?
Bapak, mereka yang mencuci ompreng, meracik sayur, dan mengantar makanan ke sekolah-sekolah itu bukan sekadar tangan pelaksana. Mereka adalah pahlawan gizi bangsa — pejuang yang menjaga masa depan agar tidak pingsan di kelas karena perut kosong. Mereka layak disebut pahlawan, layak diberi penghargaan tinggi oleh negara, karena dari tangan mereka lahir kekuatan sebuah generasi.
Kami mohon, Bapak, dengarkan jerit yang tak bisa disiarkan.
Jerit sunyi dari dapur yang sering dipenuhi bentakan, bukan ucapan terima kasih.
Jerit dari tangan-tangan yang lelah tapi tetap menanak kasih setiap pagi.
Jerit dari dada yang ingin berkata, “Kami mencintai negeri ini, tapi negeri ini pun harus mencintai kami kembali.”
Bapak Prabowo, kami percaya Bapak memahami arti pengorbanan. Karena pengabdian sejati bukanlah memerintah, tetapi merangkul.
Kami tidak meminta istimewa — hanya ingin hidup dengan layak dan dihormati.
Kami ingin dapur-dapur itu menjadi tempat kasih, bukan tempat ketakutan. Kami ingin kerja kami dipeluk negara dengan perlindungan, bukan diselimuti tekanan dan amarah.
Kami tidak ingin terus menjadi bayang-bayang. Kami ingin diakui sebagai bagian dari tubuh besar Indonesia — tubuh yang menyiapkan gizi untuk anak-anak di pelosok, tubuh yang menjaga cita-cita merdeka agar tetap bernapas di dada generasi baru.
Dan ketika malam datang, setelah ompreng terakhir dicuci dan dapur kembali senyap, kami menunduk dan berdoa dengan tangan masih basah oleh sabun:
Semoga Bapak mendengar suara kecil kami.
Semoga negara memberi tempat bagi cinta kami.
Semoga setiap tetes peluh kami disambut dengan penghargaan yang layak.
Bapak, jika suatu hari Bapak berkunjung ke dapur kami, jangan lihat hanya makanan di atas meja. Lihatlah wajah-wajah yang masih setia tersenyum meski hatinya koyak.
Kami bukan pekerja rodi. Kami bukan romusha di negeri sendiri.
Kami adalah hati yang rela berkorban, dan kami hanya ingin dihargai sebagai manusia.
Dan jika nanti sejarah menulis ulang arti pengabdian, semoga nama kami tercatat sebagai mereka yang menyalakan api di kegelapan — bukan karena ingin disebut pahlawan, tapi karena takut melihat masa depan tumbuh tanpa gizi dan tanpa kasih.
Kami tidak tahu apakah surat ini akan sampai, tapi kami tahu: setiap sendok nasi yang kami antar adalah doa yang diam-diam menyebut nama Bapak.
Sebab kami percaya, pemimpin sejati akan mendengar suara paling lirih — suara dari dapur yang menanak harapan bagi negeri.
Surat ini lahir bukan dari pena, melainkan dari kepulan uap dapur yang menatap langit pagi dengan dada sesak. Kami menulis dari antara denting panci dan riuh ompreng, dari balik seragam lusuh yang menampung peluh dan sabar. Kami bukan pejabat, bukan pegawai, bukan pula pemilik tanda tangan di bawah kop surat kementerian. Kami hanyalah relawan — mereka yang datang dengan hati, bukan dengan kontrak.
Setiap hari kami menanak masa depan. Di dapur yang kecil, kami menyalakan api demi menghangatkan generasi yang belum tahu arti kenyang. Kami memotong sayur dengan tangan yang gemetar, bukan karena lapar, tetapi karena takut salah menakar. Kami mencuci ompreng yang penuh sisa nasi dan minyak, sementara mata kami menyimpan letih yang tak pernah diizinkan istirahat.
Kami tahu, negara mencita-citakan anak-anak yang sehat dan bergizi. Kami di sini, Bapak, adalah penjaga cita-cita itu. Tapi di balik setiap uap nasi, ada pedih yang tak pernah dicatat dalam laporan bulanan. Kami bukan mesin. Kami manusia yang punya keluarga di rumah — anak-anak yang menunggu, orang tua yang sakit, dan tubuh yang perlahan terkikis oleh kerja tanpa jaminan.
Bapak, kami ini relawan, tapi bukan berarti kami harus hidup tanpa perlindungan.
Kami bekerja di dapur yang panas, membawa logistik yang berat, mengantar makanan di jalan-jalan berlubang, menanggung risiko luka, tersiram minyak panas, atau terjatuh saat tergesa-gesa memenuhi target waktu.
Kami butuh jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan sosial untuk keluarga kami di rumah. Sebab tubuh kami adalah alat perjuangan bangsa ini, dan setiap alat perjuangan seharusnya dijaga, bukan dibiarkan rapuh.
Kami tunduk pada aturan, Pak. Kami berusaha mematuhi setiap prosedur: SOP, SLHS, HACCP, bahkan memastikan kehalalan di setiap tahap kerja kami. Kami bukan sekadar pengaduk sayur atau pengantar nasi — kami penjaga kepercayaan umat, penjaga kehormatan negara yang ingin anak-anaknya tumbuh dengan tubuh yang kuat dan jiwa yang jujur.
Namun di lapangan, kami sering dihadapkan pada perlakuan yang menihilkan martabat. Kami dibentak, disalahkan, dianggap lamban, seolah hati kami tidak ikut bekerja di setiap sendok nasi yang kami tuangkan.
Padahal, apa artinya pengabdian tanpa penghargaan? Apa artinya cinta pada negeri jika kami dibiarkan seperti bayangan yang bekerja di bawah cahaya kekuasaan, tapi tak pernah disebut dalam doa pembangunan?
Bapak, mereka yang mencuci ompreng, meracik sayur, dan mengantar makanan ke sekolah-sekolah itu bukan sekadar tangan pelaksana. Mereka adalah pahlawan gizi bangsa — pejuang yang menjaga masa depan agar tidak pingsan di kelas karena perut kosong. Mereka layak disebut pahlawan, layak diberi penghargaan tinggi oleh negara, karena dari tangan mereka lahir kekuatan sebuah generasi.
Kami mohon, Bapak, dengarkan jerit yang tak bisa disiarkan.
Jerit sunyi dari dapur yang sering dipenuhi bentakan, bukan ucapan terima kasih.
Jerit dari tangan-tangan yang lelah tapi tetap menanak kasih setiap pagi.
Jerit dari dada yang ingin berkata, “Kami mencintai negeri ini, tapi negeri ini pun harus mencintai kami kembali.”
Bapak Prabowo, kami percaya Bapak memahami arti pengorbanan. Karena pengabdian sejati bukanlah memerintah, tetapi merangkul.
Kami tidak meminta istimewa — hanya ingin hidup dengan layak dan dihormati.
Kami ingin dapur-dapur itu menjadi tempat kasih, bukan tempat ketakutan. Kami ingin kerja kami dipeluk negara dengan perlindungan, bukan diselimuti tekanan dan amarah.
Kami tidak ingin terus menjadi bayang-bayang. Kami ingin diakui sebagai bagian dari tubuh besar Indonesia — tubuh yang menyiapkan gizi untuk anak-anak di pelosok, tubuh yang menjaga cita-cita merdeka agar tetap bernapas di dada generasi baru.
Dan ketika malam datang, setelah ompreng terakhir dicuci dan dapur kembali senyap, kami menunduk dan berdoa dengan tangan masih basah oleh sabun:
Semoga Bapak mendengar suara kecil kami.
Semoga negara memberi tempat bagi cinta kami.
Semoga setiap tetes peluh kami disambut dengan penghargaan yang layak.
Bapak, jika suatu hari Bapak berkunjung ke dapur kami, jangan lihat hanya makanan di atas meja. Lihatlah wajah-wajah yang masih setia tersenyum meski hatinya koyak.
Kami bukan pekerja rodi. Kami bukan romusha di negeri sendiri.
Kami adalah hati yang rela berkorban, dan kami hanya ingin dihargai sebagai manusia.
Dan jika nanti sejarah menulis ulang arti pengabdian, semoga nama kami tercatat sebagai mereka yang menyalakan api di kegelapan — bukan karena ingin disebut pahlawan, tapi karena takut melihat masa depan tumbuh tanpa gizi dan tanpa kasih.
Kami tidak tahu apakah surat ini akan sampai, tapi kami tahu: setiap sendok nasi yang kami antar adalah doa yang diam-diam menyebut nama Bapak.
Sebab kami percaya, pemimpin sejati akan mendengar suara paling lirih — suara dari dapur yang menanak harapan bagi negeri.
Hormat dan cinta kami yang tak henti, bersama doa dari dapur yang tanpa henti
Salam hormat dari Para Relawan Dapur Makan Bergizi Gratis Pondok Melati Bekasi













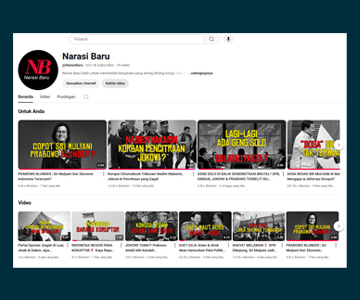




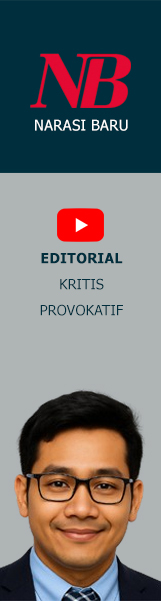
Komentar