Dalam lintasan sejarah Indonesia modern, tak ada nama yang lebih sarat kontroversi dibanding Soeharto. Selama tiga dekade lebih ia memegang kendali negeri ini, mencatat prestasi besar sekaligus meninggalkan luka mendalam. Namun sejarah, bila ingin adil, tak dapat menilai satu bab dari keseluruhan buku. Soeharto adalah bagian dari perjalanan bangsa yang penuh warna, kontradiksi, tetapi juga keteguhan yang tak terbantahkan.
Banyak yang mengingat Soeharto sebagai sosok yang dingin, penuh perhitungan, bahkan otoriter. Namun di balik citra keras itu, terdapat alasan yang sulit diabaikan. Indonesia pada pertengahan 1960-an bukanlah negeri yang damai. Politik terbagi, ekonomi terpuruk, dan masyarakat dilanda ketakutan akibat perebutan ideologi. Ketika kekacauan meledak pasca peristiwa G30S/PKI, Soeharto tampil bukan sebagai penguasa yang haus kekuasaan, melainkan sebagai sosok yang berani mengambil keputusan di tengah kevakuman otoritas. Ia menegakkan kembali keteraturan, memadamkan api ideologi komunis yang sempat membakar sendi-sendi bangsa, dan menegakkan stabilitas yang menjadi fondasi bagi pembangunan nasional.
Soeharto memahami bahwa bangsa yang tercerai-berai oleh konflik tak akan mampu membangun masa depan. Maka prioritasnya jelas: menegakkan keamanan dan stabilitas. Ia memberantas kejahatan dengan cara-cara tegas, terkadang keras, namun efektif di zamannya. Dalam periode awal pemerintahannya, tindakan disipliner terhadap penyelundupan, kriminalitas, dan korupsi di kalangan pejabat dijalankan dengan pendekatan yang nyaris militeristik. Indonesia yang sebelumnya porak-poranda, perlahan menemukan kembali arah dan kepercayaannya pada institusi negara.
Kemudian datang masa yang oleh banyak orang disebut sebagai “masa keemasan pembangunan.” Di bawah bendera Orde Baru, Soeharto membangun Indonesia dari fondasi yang sederhana menuju ekonomi yang lebih terencana. Swasembada beras tahun 1984 bukan sekadar capaian statistic, itu adalah simbol kedaulatan pangan yang membuat bangsa ini berdiri sejajar dengan negara lain. Desa-desa yang sebelumnya gelap mulai diterangi listrik; jalan, jembatan, dan waduk dibangun; dan transmigrasi membuka harapan baru bagi jutaan rakyat.
Ia juga memperkuat peran militer bukan hanya sebagai kekuatan keamanan, tetapi juga alat pembangunan. ABRI kala itu ditempatkan sebagai penjaga stabilitas sekaligus pelaksana pembangunan di daerah-daerah terpencil. Di bidang pendidikan, Soeharto memperluas akses sekolah dasar melalui program Wajib Belajar, membuka pintu bagi generasi muda untuk mengenal dunia modern tanpa tercerabut dari akar kebangsaan.
Namun jasa terbesar Soeharto mungkin terletak pada visinya terhadap kedaulatan nasional. Di tengah tekanan global dan ketegangan Perang Dingin, ia mampu menjaga Indonesia agar tetap berdiri di tengah, tidak sepenuhnya condong ke blok manapun. Politik luar negeri “bebas aktif” dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Indonesia menjadi bagian penting dalam berdirinya ASEAN, memperkuat diplomasi regional yang hingga kini menjadi fondasi politik luar negeri kita.
Tentu, tidak ada pemimpin tanpa kekurangan. Otoritarianisme, pembatasan kebebasan pers, praktik KKN, dan ketimpangan ekonomi adalah catatan kelam yang melekat pada masa pemerintahannya. Namun yang perlu kita renungkan: kesalahan itu muncul dari sistem yang dibangun untuk tujuan stabilitas, bukan sekadar demi kekuasaan pribadi. Ia membangun dari keteraturan, meski terkadang keteraturan itu mengorbankan kebebasan.
Kini, dua dekade lebih setelah akhir kekuasaannya, bangsa ini masih terus mencari keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban, antara demokrasi dan efektivitas. Reformasi membawa banyak kemajuan, tetapi juga kebisingan politik tanpa arah yang jelas. Dalam konteks itu, nama Soeharto kembali bergema bukan dalam kerinduan akan otoritarianisme, tetapi dalam kerinduan akan kepemimpinan yang berani mengambil keputusan dan mampu menjaga arah bangsa.
Menilai Soeharto secara jujur berarti mengakui bahwa Indonesia hari ini berdiri di atas fondasi yang ia bangun. Dari sawah yang hijau di Jawa hingga jembatan megah di Sumatera, dari waduk di Sulawesi hingga sekolah di pelosok Papua, jejaknya masih benar-benar nyata. Ia membentuk cara kita berpikir tentang negara, tentang pembangunan, tentang disiplin dan ketertiban.
Sejarah memang tidak menulis manusia dalam warna tunggal. Soeharto bukan malaikat, tetapi ia juga bukan setan. Ia adalah manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, seorang prajurit yang membawa disiplin militer ke panggung pemerintahan, seorang bapak yang keras tetapi ingin anak-anaknya (rakyatnya) tidak kelaparan dan tidak tercerai-berai.
Kini, tugas kita bukan sekadar memuja atau mencaci, melainkan belajar. Dari ketegasan Soeharto, kita belajar pentingnya kepemimpinan yang berani. Dari kesalahannya, kita belajar bahwa kekuasaan tanpa kontrol bisa berbahaya. Dan dari warisannya, kita tahu bahwa membangun bangsa tidak cukup dengan kata-kata, tetapi dengan kerja nyata, visi, dan keberanian untuk menanggung konsekuensi.
Karena pada akhirnya, sejarah tidak diukur dari berapa banyak orang berteriak di jalan, tetapi dari seberapa kokoh sebuah bangsa berdiri setelah badai berlalu. Dan dalam ukuran itu, nama Soeharto akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan Indonesia yang panjang dan berliku.














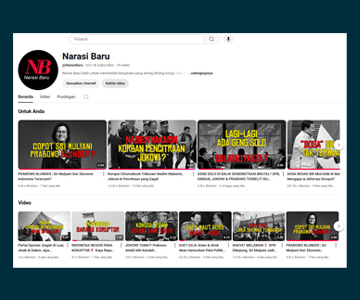




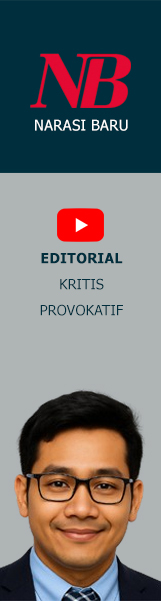
Komentar